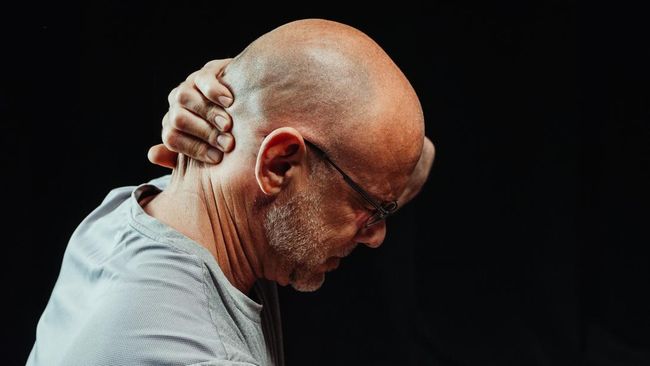JAKARTA, ILLINI NEWS – Fenomena pasangan “hidup bersama” yang hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah semakin marak di Indonesia. Hal ini terjadi ketika norma hukum dan agama tidak sejalan dengan hal tersebut.
Seperti dilansir The Conversation, salah satu alasan kaum muda memutuskan untuk hidup bersama tanpa menikah atau bersama pasangan adalah perubahan sikap terhadap hubungan dan pernikahan.
Hanya sedikit generasi muda saat ini yang memandang pernikahan sebagai urusan formal dengan aturan yang rumit. Sebaliknya, mereka melihat “hidup bersama” sebagai hubungan murni dan bentuk cinta sejati.
Orang-orang dari Eropa Barat dan Utara, Amerika, Kanada, Australia dan Selandia Baru yang menghormati budaya, tradisi dan agama Asia tidak menerima pengakuan hukum atas “hidup berdampingan”. Kalaupun terjadi, “hidup bersama” hanya untuk waktu yang singkat dan dianggap sebagai langkah awal menuju pernikahan.
Menurut penelitian bertajuk The Untold Story of Coexistence in Indonesia 2021, “hidup berdampingan” paling banyak terjadi di Indonesia bagian timur, yang mayoritas penduduknya non-Muslim.
Menurut Yulinda Nurul Aini, peneliti ahli muda Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setidaknya ada tiga alasan pasangan di Manado, lokasi penelitiannya, memilih “tinggal” bersama pasangannya. Beban keuangan, prosedur perceraian yang lebih rumit dan penerimaan sosial.
Analisis saya terhadap data Dataset Rumah Tangga (PK21) tahun 2021 milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan 0,6 persen penduduk Manado, Sulawesi Utara tinggal bersama, kata Yulinda. Dikutip pada Minggu (3/11/2024).
“Dari semua pasangan yang tinggal bersama, 1,9 persen sedang hamil pada saat survei, 24,3 persen berusia di bawah 30 tahun, 83,7 persen berpendidikan sekolah menengah atas atau kurang, 11,6 persen menganggur dan 53 persen, serta 5 persen bekerja. secara informal” lanjutnya. Pengaruh Kumpul Kebo
Yulinda mengatakan, yang paling terkena dampak negatif dari “hidup berdampingan” adalah perempuan dan anak-anak. Tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu sebagaimana tertuang dalam undang-undang perceraian dalam konteks ekonomi. Dalam hidup bersama, sang ayah tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan dukungan finansial dalam bentuk nafkah.
“Ketika pasangan suami istri berpisah, tidak ada kerangka peraturan yang mengatur pembagian harta dan keuangan, tunjangan, hak waris, hak asuh anak dan masalah lainnya,” jelas Yulinda.
Sedangkan dari segi kesehatan, “kohabitasi” dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah dampak negatif dari hidup bersama antara lain kurangnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan serta ketidakpastian tentang masa depan.
Berdasarkan data KP21, 69,1 persen pasangan kumpul kebo pernah mengalami konflik berjenis kutukan, 0,62 persen pernah mengalami konflik berat seperti berbagi tempat tidur dan tempat tinggal, serta 0,26 persen lainnya pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Selanjutnya, anak yang lahir dari hubungan kumpul kebo mengalami gangguan tumbuh kembang, kesehatan, dan emosi.
“Anak-anak dapat mengalami kebingungan identitas akibat stigma dan diskriminasi yang mereka hadapi atas statusnya sebagai ‘anak haram’ dan diskriminasi bahkan oleh anggota keluarganya sendiri,” kata Yulinda.
“Hal ini membuat sulit untuk menempatkan mereka dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya. (fys/wur) Tonton video di bawah ini: Video: Produsen parfum lokal ‘berebut’ pasar karena daya beli melemah